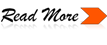Oleh Al. Wisnubroto *)
[29/7/09]
Joko Tjandra dan Sjahril Sabirin bisa jadi merasa geram terhadap putusan Mahkamah Agung RI atas “PK (Peninjauan Kembali) Kontroversial” yang membatalkan Putusan Kasasi MA yang telah membebaskannya.
Tidak hanya mereka, sejumlah kalangan praktisi hukum dan akademisi pun serentak mengecam Putusan MA yang menerima PK yang diajukan oleh Jaksa tersebut (http://hukumonline.com/detail.asp?id=22669&cl=Berita). PK tersebut dinilai kontroversial karena diajukan oleh Jaksa, yang berarti tidak sesuai ketentuan dalam KUHAP. Oleh sebab itu Tim Penasehat Hukumnya berniat melawan putusan tersebut dengan upaya hukum yang tak kalah kontroversialnya yakni PK atas PK.
PK Kontroversial merupakan istilah yang dipilih penulis untuk menunjuk upaya hukum PK yang tidak lazim dan menimbulkan pandangan pro-kontra. Setidaknya ada tiga jenis PK yang digolongkan sebagai kontroversial yakni: PK yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum; PK atas PK dan PK yang diajukan lebih dari satu kali.
Ketiga PK tersebut dipandang kontroversial karena sebagian ahli hukum memandang PK tersebut menyimpang dari hukum positif (KUHAP), merusak sistem hukum acara, bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan menimbulkan potensi kesewenang-wenangan aparatur negara terhadap warga negara (dalam hal ini terpidana).
Aturan hukum positif tentang PK sendiri nampak memiliki keterbatasan dan bersifat multitafsir. Pasal 263 ayat (1) KUHAP secara eksplisit menetapkan bahwa PK merupakan hak terpidana dan ahli warisnya. Namun dalam KUHAP tidak ada ketentuan yang melarang Jaksa Penuntut Umum mengajukan PK, apakah terhadap putusan PK dapat dilawan dengan PK atau upaya hukum lainnya, dan berapa kali PK dalam perkara pidana bisa diajukan untuk perkara yang sama. Kevakuman hukum ini sering dimanfaatkan oleh para pihak dengan masing-masing kepentingan dan penafsirannya untuk mengajukan PK yang kontroversial.
Filosofi melindungi pihak yang lemah
Konon KUHAP dibangun dengan filosofi perlindungan bagi pihak yang lemah dan rentan terhadap kekuasaan negara. Bila kekuasaan negara dalam sistem peradilan pidana dipahami sebagai aparatur penegak hukum yang dalam menjalankan tugasnya memiliki kewenangan yang amat besar, maka wajar bila KUHAP cenderung mengutamakan aturan mengenai hak-hak tersangka, terdakwa atau terpidana dan pembatasan kewenangan aparatur penegak hukum.
Dalam paradigma yang demikian maka tidak salah bila KUHAP mengatur bahwa PK merupakan hak bagi terpidana dan ahli warisnya sebagai pihak yang lemah dan rentan terhadap proses peradilan yang keliru. Demikian pula keberadaan asas “aturan yang menguntungkan bagi terdakwa” dalam sistem hukum pidana harus diletakkan dalam konteks ini. Jaksa tidak diatur haknya untuk PK dengan asumsi bahwa sebagai pihak yang mewakili negara dalam perkara pidana, jaksa telah diberikan kewenangan yang amat besar untuk membuktikan kesalahan terdakwa selama proses peradilan berlangsung.
Persoalannya muncul bila dikaitkan dengan kepentingan korban yang bisa jadi posisinya paling lemah dalam proses peradilan pidana. Para ahli hukum sendiri pada akhirnya mengakui bahwa KUHAP hampir tidak mengakomodasi kepentingan korban tindak pidana, sehingga perlindungan korban terpaksa harus dibuatkan undang-undang tersendiri yakni Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Dalam kasus-kasus kejahatan tertentu seringkali pelaku kejahatan memiliki kekuatan amat besar untuk memperdaya korban-korbannya, bahkan untuk menghadapi aparatur penegak hukum. Katakanlah kejahatan yang secara sistematis berkonspirasi dengan kekuatan politik dan ekonomi. Dalam keadaan demikian justru korban, masyarakat, aparatur hukum bahkan negara seringkali justru berada dalam posisi pihak yang lemah dan rentan terhadap manipulasi sistem hukum.
Korban, baik sebagai individu maupun masyarakat tentu juga memiliki hak untuk memperoleh keadilan termasuk untuk mengoreksi putusan tingkat apapun yang dinilai tidak adil. Dalam konsep peradilan negara, kepentingan korban telah diambil alih oleh Jaksa. Karena dalam sistem peradilan pidana korban tidak dimungkinkan secara langsung untuk menuntut pelaku tindak pidana, maka sebagai konsekuensinya Jaksa harus melayani kepentingan korban, termasuk mengajukan PK guna meraih keadilan yang sejati.
Butuh “Katup” Pengecualian
Untuk menegakkan kepastian hukum maka harus ada konsep pembatasan yang tegas terhadap tahap-tahap pengajuan upaya hukum. Namun demikian hak untuk menggapai keadilan harus dibuka seluas-luasnya yakni bila terdapat alasan yang secara rasional dan moral dapat dipertanggungjawabkan. Keduanya (kepastian dan keadilan) merupakan prinsip yang harus dipahami secara utuh bukan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Artinya kepastian hukum diperlukan dalam konteks pencapaian keadilan.
Dalam hal demikian pandangan legisme hukum atau legal-positivistik yang terlalu bersandar pada bunyi undang-undang demi kepastian hukum semata, sudah tidak memadai lagi sebagai instrumen pencapaian keadilan pada kasus-kasus yang kompleks dan bergeser dari asumsi yang dibangun saat perumusan undang-undang.
Bahwa keberadaan hukum positif (KUHAP) adalah tetap penting, akan tetapi penerapannya harus terbuka terhadap penafsiran yang progresif dan responsif.
Argumentasi ilmiahnya didasarkan pada logika empiris bahwa sebuah hukum positif selalu memiliki keterbatasan ruang dan waktu. Oleh sebab itu bila suatu ketika terjadi kebuntuan dalam mewujudkan tujuan pencapaian keadilan, maka harus dibuatkan suatu “katup” untuk membuka pengecualian terhadap kasus yang “tidak biasa” (anomali). Dalam pandangan hukum progresif, hukum tidak boleh didasarkan pada logika undang-undang semata, namun lebih dari itu harus bersandar pula pada esensi kemanusiaan yang didalamnya terdapat pertimbangan nurani, moral, empati dan integritas.
Apa yang dimaksud dengan “pengecualian” tidak boleh disalahtafsirkan sebagai “penyimpangan” atau “kesewenang-wenangan”, karena dalam sebuah pengecualian terdapat pertimbangan nilai-nilai fundamental melebihi pertimbangan yuridis-prakmatis. Dalam sistem hukum yang telah mapan diberbagai negara maju-pun dikenal adanya pengecualian sebagai alternatif penyelesaian perkara yang bahkan beberapa diantaranya bila dilihat dari pemahaman sistem hukum (positif) kita bisa dicurigai sebagai “penyimpangan”.
Dalam kasus-kasus yang “tidak biasa” seperti extra-ordinary crimes (misal: Kejahatan Lingkungan, Korupsi, Pelanggaran HAM berat) yang umumnya dilakukan oleh “pihak yang kuat” dan menimbulkan dampak serius bagi warga negara/masyarakat yang dalam hal ini pada posisi “pihak yang lemah” serta memiliki tingkat pembuktian yang sulit, maka demi pencapaian keadilan yang substantif PK oleh Jaksa yang melayani warga negara/masyarakat harus dipandang sebagai pengecualian.
Jadi dalam keadaan “normal”, aturan bahwa PK adalah hak terpidana dan ahli warisnya adalah prinsip yang harus ditegakkan. Namun bila keadaannya bersifat “anomali” harus ada sebuah pengecualian guna membuka kebuntuan hukum dalam pencapaian keadilan. Prinsip progresif dalam pengecualian PK kontroversial ini berlaku pula untuk PK atas PK dan PK yang diajukan lebih dari dua kali. Bila pengecualian yang berupa terobosan hukum (rule breaking) tersebut dipandang bisa memberikan keadilan yang substansial, maka ke depan seyogyanya pengecualian tersebut bisa diintegrasikan pada penyempurnaan aturan PK dalam hukum positif (KUHAP), agar tidak ada persoalan lagi pada kepastian hukumnya.
--------
*) Penulis adalah pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Anggota Serikat Pekerja Hukum Progresif
Selengkapnya...
[29/7/09]
Joko Tjandra dan Sjahril Sabirin bisa jadi merasa geram terhadap putusan Mahkamah Agung RI atas “PK (Peninjauan Kembali) Kontroversial” yang membatalkan Putusan Kasasi MA yang telah membebaskannya.
Tidak hanya mereka, sejumlah kalangan praktisi hukum dan akademisi pun serentak mengecam Putusan MA yang menerima PK yang diajukan oleh Jaksa tersebut (http://hukumonline.com/detail.asp?id=22669&cl=Berita). PK tersebut dinilai kontroversial karena diajukan oleh Jaksa, yang berarti tidak sesuai ketentuan dalam KUHAP. Oleh sebab itu Tim Penasehat Hukumnya berniat melawan putusan tersebut dengan upaya hukum yang tak kalah kontroversialnya yakni PK atas PK.
PK Kontroversial merupakan istilah yang dipilih penulis untuk menunjuk upaya hukum PK yang tidak lazim dan menimbulkan pandangan pro-kontra. Setidaknya ada tiga jenis PK yang digolongkan sebagai kontroversial yakni: PK yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum; PK atas PK dan PK yang diajukan lebih dari satu kali.
Ketiga PK tersebut dipandang kontroversial karena sebagian ahli hukum memandang PK tersebut menyimpang dari hukum positif (KUHAP), merusak sistem hukum acara, bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan menimbulkan potensi kesewenang-wenangan aparatur negara terhadap warga negara (dalam hal ini terpidana).
Aturan hukum positif tentang PK sendiri nampak memiliki keterbatasan dan bersifat multitafsir. Pasal 263 ayat (1) KUHAP secara eksplisit menetapkan bahwa PK merupakan hak terpidana dan ahli warisnya. Namun dalam KUHAP tidak ada ketentuan yang melarang Jaksa Penuntut Umum mengajukan PK, apakah terhadap putusan PK dapat dilawan dengan PK atau upaya hukum lainnya, dan berapa kali PK dalam perkara pidana bisa diajukan untuk perkara yang sama. Kevakuman hukum ini sering dimanfaatkan oleh para pihak dengan masing-masing kepentingan dan penafsirannya untuk mengajukan PK yang kontroversial.
Filosofi melindungi pihak yang lemah
Konon KUHAP dibangun dengan filosofi perlindungan bagi pihak yang lemah dan rentan terhadap kekuasaan negara. Bila kekuasaan negara dalam sistem peradilan pidana dipahami sebagai aparatur penegak hukum yang dalam menjalankan tugasnya memiliki kewenangan yang amat besar, maka wajar bila KUHAP cenderung mengutamakan aturan mengenai hak-hak tersangka, terdakwa atau terpidana dan pembatasan kewenangan aparatur penegak hukum.
Dalam paradigma yang demikian maka tidak salah bila KUHAP mengatur bahwa PK merupakan hak bagi terpidana dan ahli warisnya sebagai pihak yang lemah dan rentan terhadap proses peradilan yang keliru. Demikian pula keberadaan asas “aturan yang menguntungkan bagi terdakwa” dalam sistem hukum pidana harus diletakkan dalam konteks ini. Jaksa tidak diatur haknya untuk PK dengan asumsi bahwa sebagai pihak yang mewakili negara dalam perkara pidana, jaksa telah diberikan kewenangan yang amat besar untuk membuktikan kesalahan terdakwa selama proses peradilan berlangsung.
Persoalannya muncul bila dikaitkan dengan kepentingan korban yang bisa jadi posisinya paling lemah dalam proses peradilan pidana. Para ahli hukum sendiri pada akhirnya mengakui bahwa KUHAP hampir tidak mengakomodasi kepentingan korban tindak pidana, sehingga perlindungan korban terpaksa harus dibuatkan undang-undang tersendiri yakni Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Dalam kasus-kasus kejahatan tertentu seringkali pelaku kejahatan memiliki kekuatan amat besar untuk memperdaya korban-korbannya, bahkan untuk menghadapi aparatur penegak hukum. Katakanlah kejahatan yang secara sistematis berkonspirasi dengan kekuatan politik dan ekonomi. Dalam keadaan demikian justru korban, masyarakat, aparatur hukum bahkan negara seringkali justru berada dalam posisi pihak yang lemah dan rentan terhadap manipulasi sistem hukum.
Korban, baik sebagai individu maupun masyarakat tentu juga memiliki hak untuk memperoleh keadilan termasuk untuk mengoreksi putusan tingkat apapun yang dinilai tidak adil. Dalam konsep peradilan negara, kepentingan korban telah diambil alih oleh Jaksa. Karena dalam sistem peradilan pidana korban tidak dimungkinkan secara langsung untuk menuntut pelaku tindak pidana, maka sebagai konsekuensinya Jaksa harus melayani kepentingan korban, termasuk mengajukan PK guna meraih keadilan yang sejati.
Butuh “Katup” Pengecualian
Untuk menegakkan kepastian hukum maka harus ada konsep pembatasan yang tegas terhadap tahap-tahap pengajuan upaya hukum. Namun demikian hak untuk menggapai keadilan harus dibuka seluas-luasnya yakni bila terdapat alasan yang secara rasional dan moral dapat dipertanggungjawabkan. Keduanya (kepastian dan keadilan) merupakan prinsip yang harus dipahami secara utuh bukan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Artinya kepastian hukum diperlukan dalam konteks pencapaian keadilan.
Dalam hal demikian pandangan legisme hukum atau legal-positivistik yang terlalu bersandar pada bunyi undang-undang demi kepastian hukum semata, sudah tidak memadai lagi sebagai instrumen pencapaian keadilan pada kasus-kasus yang kompleks dan bergeser dari asumsi yang dibangun saat perumusan undang-undang.
Bahwa keberadaan hukum positif (KUHAP) adalah tetap penting, akan tetapi penerapannya harus terbuka terhadap penafsiran yang progresif dan responsif.
Argumentasi ilmiahnya didasarkan pada logika empiris bahwa sebuah hukum positif selalu memiliki keterbatasan ruang dan waktu. Oleh sebab itu bila suatu ketika terjadi kebuntuan dalam mewujudkan tujuan pencapaian keadilan, maka harus dibuatkan suatu “katup” untuk membuka pengecualian terhadap kasus yang “tidak biasa” (anomali). Dalam pandangan hukum progresif, hukum tidak boleh didasarkan pada logika undang-undang semata, namun lebih dari itu harus bersandar pula pada esensi kemanusiaan yang didalamnya terdapat pertimbangan nurani, moral, empati dan integritas.
Apa yang dimaksud dengan “pengecualian” tidak boleh disalahtafsirkan sebagai “penyimpangan” atau “kesewenang-wenangan”, karena dalam sebuah pengecualian terdapat pertimbangan nilai-nilai fundamental melebihi pertimbangan yuridis-prakmatis. Dalam sistem hukum yang telah mapan diberbagai negara maju-pun dikenal adanya pengecualian sebagai alternatif penyelesaian perkara yang bahkan beberapa diantaranya bila dilihat dari pemahaman sistem hukum (positif) kita bisa dicurigai sebagai “penyimpangan”.
Dalam kasus-kasus yang “tidak biasa” seperti extra-ordinary crimes (misal: Kejahatan Lingkungan, Korupsi, Pelanggaran HAM berat) yang umumnya dilakukan oleh “pihak yang kuat” dan menimbulkan dampak serius bagi warga negara/masyarakat yang dalam hal ini pada posisi “pihak yang lemah” serta memiliki tingkat pembuktian yang sulit, maka demi pencapaian keadilan yang substantif PK oleh Jaksa yang melayani warga negara/masyarakat harus dipandang sebagai pengecualian.
Jadi dalam keadaan “normal”, aturan bahwa PK adalah hak terpidana dan ahli warisnya adalah prinsip yang harus ditegakkan. Namun bila keadaannya bersifat “anomali” harus ada sebuah pengecualian guna membuka kebuntuan hukum dalam pencapaian keadilan. Prinsip progresif dalam pengecualian PK kontroversial ini berlaku pula untuk PK atas PK dan PK yang diajukan lebih dari dua kali. Bila pengecualian yang berupa terobosan hukum (rule breaking) tersebut dipandang bisa memberikan keadilan yang substansial, maka ke depan seyogyanya pengecualian tersebut bisa diintegrasikan pada penyempurnaan aturan PK dalam hukum positif (KUHAP), agar tidak ada persoalan lagi pada kepastian hukumnya.
--------
*) Penulis adalah pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Anggota Serikat Pekerja Hukum Progresif